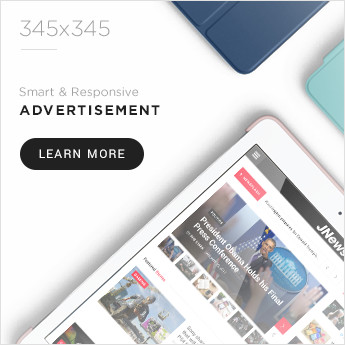AsamManis.news, 9 Oktober 2025 – Media sosial semestinya menjadi ruang baru yang sehat bagi publik untuk menyalurkan kritik dan pandangan terhadap kebijakan negara. Dalam sistem demokrasi, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam diskursus publik adalah pilar penting. Namun, di era digital saat ini, ruang ekspresi itu kerap melenceng dari fungsinya: dari forum pertukaran gagasan menjadi arena perundungan dan kekerasan verbal.
Salah satu contohnya adalah fenomena body shaming yang dialami Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Alih-alih mengkritisi substansi kebijakan energi atau langkah strategis pemerintah, sebagian warganet justru memilih menyerang hal-hal personal seperti penampilan fisik dan gaya bicara sang menteri. Fenomena ini menandakan adanya krisis etika dalam praktik demokrasi digital di Indonesia.
Padahal, posisi strategis Menteri ESDM berkaitan langsung dengan berbagai isu nasional: dari harga bahan bakar, pengelolaan tambang, hingga transisi menuju energi baru dan terbarukan. Kritik tentu wajar dan perlu dalam iklim demokrasi. Namun, ketika kritik bergeser menjadi hinaan fisik, diskusi publik kehilangan nilai intelektualnya dan terjerumus pada kebencian yang dangkal.
Ironisnya, sebagian pelaku perundungan verbal ini merasa sedang “menyuarakan pendapat”. Padahal, body shaming bukanlah bentuk kritik—itu adalah kekerasan. Terlebih lagi jika dilakukan di ruang publik digital yang dapat menyebar dengan cepat dan meninggalkan jejak permanen. Ini menjadi bukti bahwa literasi digital kita masih dangkal—bukan hanya dalam aspek teknis, tetapi terutama dalam aspek etika dan empati.
Kapasitas seorang pejabat publik tidak bisa diukur dari penampilan fisik atau aksen berbicara, melainkan dari kualitas kebijakan dan keberpihakannya pada kepentingan rakyat. Namun di tengah dominasi algoritma media sosial yang lebih menyukai sensasi ketimbang substansi, komentar dangkal kerap lebih viral dibanding kritik yang berbasis data dan argumen.
Krisis etika ini bukan hanya merugikan individu seperti Menteri Bahlil, tetapi juga menggerus kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi publik yang cerdas dan beradab—bukan cacian, tapi koreksi yang konstruktif. Jika ruang digital terus dibiarkan menjadi tempat menghina, maka kita tidak sedang membangun demokrasi, melainkan memperkuat budaya kebencian.
Lebih dari itu, peristiwa ini memperlihatkan kontradiksi dalam karakter sosial bangsa kita. Di satu sisi, Indonesia dikenal dengan budaya sopan santun dan nilai kekeluargaan yang tinggi. Namun di dunia maya, sopan santun itu kerap menguap—berganti dengan komentar kasar kepada orang yang bahkan tak dikenal secara pribadi. Kita seakan lupa bahwa di balik layar gawai, masih ada manusia yang bisa terluka oleh kata-kata.
Sudah saatnya kita menata ulang cara kita berkomunikasi di era digital. Kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan untuk menghina. Kritik yang elegan, berbasis data, dan disampaikan dengan bahasa yang santun, justru lebih berdampak dalam mendorong perubahan. Ruang digital seharusnya menjadi taman dialog, bukan ladang pertempuran.
Kasus body shaming terhadap Menteri ESDM ini bukan sekadar persoalan personal, tetapi refleksi dari budaya digital kita yang masih jauh dari matang. Ini menjadi momentum untuk membangun literasi digital yang menyeluruh—bukan hanya soal bagaimana menggunakan media sosial, tetapi bagaimana bersikap di dalamnya.
Demokrasi tidak diukur dari seberapa keras kita berteriak, tapi seberapa dewasa kita bisa berdialog. Jika bangsa ini ingin maju, maka ruang publiknya pun harus naik kelas—dari cercaan menjadi percakapan, dari body shaming menjadi argumentasi yang beradab. AM.N-001