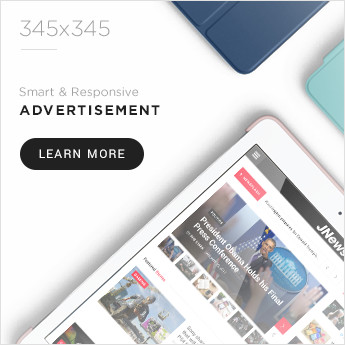Jakarta, asammanis.news, 5 Oktober 2025 – Bicara politik Indonesia hari ini, rasanya seperti menyeruput secangkir kopi pahit. Tak semua orang bisa menikmatinya. Ada yang langsung menolak, ada pula yang justru menemukan kenikmatan di balik getirnya. Begitu pula dengan politik: keras, penuh intrik, namun di situlah nilai keteguhan diuji.
Salah satu sosok yang mencuri perhatian dalam lanskap itu adalah Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar. Dalam forum Diklat Kader Muda Nasional AMPG pada 3 Oktober 2025, ia menyampaikan sesuatu yang sederhana namun sarat makna. Ia berbicara tentang perjuangannya menembus dunia politik yang seringkali eksklusif, dan bagaimana ia sudah “dikepung elite,” dijegal, serta dipinggirkan.
Namun alih-alih mengeluh, Bahlil menanggapinya dengan tawa kecil: “Om suka itu. Om suka!”
Sebuah kalimat ringan yang, jika dicermati, memuat filosofi hidup yang dalam — tentang ketabahan, daya tahan, dan seni menikmati pahitnya perjuangan.
Pernyataan Bahlil sejatinya bukan sekadar cerita pribadi. Ia mencerminkan realitas sistemik politik kita: bahwa jalan menuju puncak kekuasaan masih belum terbuka lebar bagi semua orang. Akses politik di Indonesia seringkali ditentukan oleh trah, modal, dan koneksi. Mereka yang datang dari luar lingkaran elite harus menempuh jalan lebih terjal — sendirian, bahkan kadang tanpa peta.
Dalam konteks itu, perjalanan Bahlil menjadi anomali. Ia bukan anak jenderal, bukan anak konglomerat, bukan pewaris politik. Ia berasal dari Papua — daerah yang selama ini lebih sering menjadi penonton di panggung politik nasional ketimbang pemeran utama. Ia menembus sistem bukan karena privilege, tapi karena proses panjang yang ditempuh dengan sabar.
Pesan terkuat dari pidato Bahlil bukan sekadar soal asal-usulnya, melainkan soal cara berpikirnya: bahwa politik seharusnya dinikmati sebagai proses, bukan hasil instan. Di era di mana popularitas lebih penting dari substansi, dan pencitraan menutupi rekam jejak, ajakan untuk menikmati proses terasa seperti udara segar.
Kepemimpinan yang sejati, kata Bahlil, tumbuh dari jatuh-bangun, bukan dari panggung yang dibangun semalam. Kalimat ini menampar keras budaya politik kita yang kini lebih sering mengidolakan viralitas ketimbang nilai. Banyak politisi muda hari ini lebih sibuk mencari sorotan kamera ketimbang gagasan. Dalam situasi seperti itu, mengingatkan pentingnya proses adalah bentuk perlawanan kultural.
Di sisi lain, Bahlil juga menyentil persoalan klasik dalam tubuh politik Indonesia: pewarisan kekuasaan.
“Tidak ada lagi ini anak jenderal, anak konglomerat, anak menteri,” katanya.
Ini bukan sekadar slogan, tapi kritik lembut terhadap sistem yang masih terlalu elitis. Di beberapa partai, jabatan politik masih diwariskan, bukan diperebutkan secara terbuka. Dalam sistem seperti itu, munculnya sosok seperti Bahlil adalah pengecualian, sekaligus bukti bahwa perubahan tetap mungkin.
Ia menjadi bukti hidup bahwa politik tidak harus selalu digerakkan dari atas. Bahwa perjuangan dari bawah, dari pinggiran, bisa pula menembus pusat. Ia tidak hanya menjadi simbol bagi Golkar, tetapi juga bagi jutaan anak muda dari daerah yang sering merasa tak punya akses pada kekuasaan.
Konteks asal-usul Bahlil menjadikan kisah ini semakin bermakna. Papua, tempat ia berasal, selama ini berada di pinggiran peta kekuasaan nasional. Maka ketika seorang putra Papua mampu mencapai posisi puncak politik nasional, itu bukan sekadar capaian pribadi — itu tanda bahwa politik Indonesia masih punya ruang bagi perubahan sosial yang autentik.
Namun tentu, ini bukan glorifikasi terhadap satu figur. Tokoh bisa naik, bisa pula turun. Yang penting adalah nilai perjuangan yang ditinggalkannya. Politik kita tidak kekurangan figur, tetapi sering kekurangan narasi yang menginspirasi: narasi tentang keberanian menembus batas, tentang kejujuran menghadapi kenyataan, dan tentang kapasitas yang tumbuh dari keterbatasan.
Pada akhirnya, politik memang tidak selalu manis. Tapi seperti kopi pahit, justru rasa getirnya yang membuat kita sadar bahwa kenikmatan sejati tidak datang dari kemewahan, melainkan dari perjuangan.
Bahlil Lahadalia, dengan segala keterbatasan dan kontroversinya, telah memberi pelajaran penting: bahwa dikepung elite bukan alasan untuk menyerah, melainkan energi untuk terus melangkah. Dalam setiap tegukan pahit, ada rasa yang membekas — dan mungkin di situlah esensi sejati dari politik yang manusiawi. AM.N-001